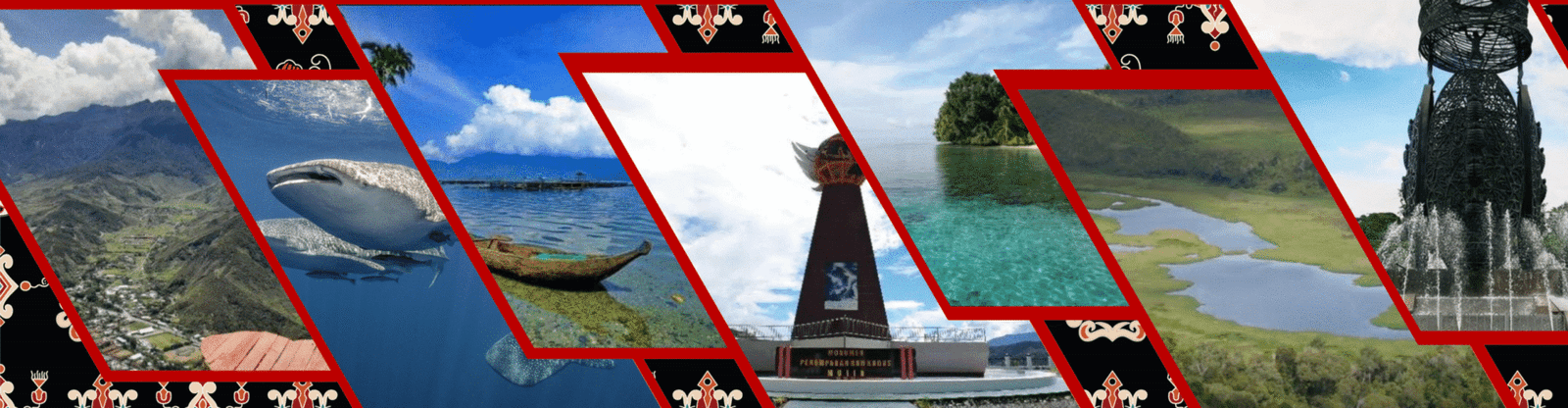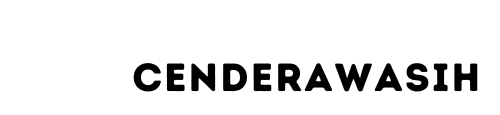Cerita Tentang Seorang Mahasiswa, Aktivis juga Pengelolah Kafe

Foto: Julia Opky
Oleh: Jhon Gobai
Saat itu Ia merasakan betapa sangat membutuhkan satu, dua orang kawan. Hal itu membuatnya hampir patah semangat. Belum lagi peserta dikpol yang datang terlambat, dst. “Tetapi saat itu saya lebih banyak mendengarkan lagu-lagu perjuangan. Lagu yang sering Saya putar berulang kali itu Judulnya: Doa Ibu di Revolusi.” Ungkapnya, tangis pecah seketika.
Saya memilih diam, membiarkan suasana ini berlalu begitu saja.
“Entah kenapa air mata Saya ini sulit dibendung, saat itu juga. Tapi Saya segera lagi ke kamar mandi untuk sudahi kesedihan ini.” Diam sejenak. Tangannya masih memegang ujung kerak baju sambil menyekah air matanya. “Mama sudah pergi jauh. Dia pasti tersenyum dengan semua yang Saya lakukan untuk banyak orang, saat ini. Saya tidak menyadari akan seliar itu situasi kesedihan ini. Tetapi Saya betul-betul membutuhkan kawan, saat itu.” Jelasnya sambil menyekah pipihnya.
Diam adalah jawaban dari Saya untuk saat itu.
***
Julia Opki. Kawan-kawannya memanggil Jo. Seorang perempuan asal suatu kota yang letaknya ujung sepanjang pegunungan Kartenz, tepatnya di perbatasan Provinsi Papua dan Negara Papua New Guinea (PNG). Lantas Ia disebut kota di atas awan, yaitu Kab. Pegunungan Bintang.
Ia dilahirkan dari wilayah konflik, tentu mengalangi tekanan psikologi juga fisiologi. Disisi lain Ia tumbuh, berkembang di bawa budaya patriarki yang subur di Papua. Jo sebagai mahasiswa, aktif juga di organisasi progresif mahasiswa di luar Kampus. Selain itu juga pengelolah kafe, yang berlokasi di Timoho. Persisnya dibelakang Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta; delapan ratus kilo meter ke utara dari rel kareta.
Suatu sore, dibawa senjah penuhi langit, disaat waktu Suarya hendak berpamit pulang, cerita hangat begitu mengalir dipandu oleh beberapa pertanyaan dasar sambil menikmati kopi asal Pegunungan Bintang, Kopi asal kampung halamannya, yang baru saja Ia sajikan.
Sejak sore Kafe itu sudah mulai ramai. Tentu unik. Disetiap tiang terdapat beberapa lukisan yang sengaja dipajang. Kursi dan Meja yang terbuat dari kayu tampak tersusun rapih sejak tadi. Sejumlah buku digantungkan ditengah, seakan memayungi setiap pengunjung yang datang berdiskusi, pacaran, atau keunikannya.
Sore itu Jo sedang sibuk melayani para pengunjung. Sementara Saya mengambil meja kosong di pojok kiri, tepat dibawa pohon Gersen.
Belum lama duduk, perempuan beramput hitam, keriting, itu berjalan ke arah Saya. Hari ini Ia kepang rambut ke belakang. Dengan celana Jeans yang sedikit menmengetat dengan begitu sangat terlihat jelas kakinya berukuran kecil; betis yang sedikit mulus, tinggi. Dan Baju rasta bergambar bob Marley yang Ia kenakan agak lebih besar dari ukuran tubuhnya sehingga silirnya angin sore itu tentu membiarkannya Ia terkibat begitu saja.
“Hai, my Brow, Kamu sudah tiba?”
“Baru saja duduk disini, Jo. Maaf telat seperempat jam. Tidak sesuai perjanjian awal di kemaring.”
“Santui bro. Saya juga mengurusi beberapa pekerjaan, tadi. Baru juga saja selesai nih.”
“Makasih untuk waktunya, Bro.”
Ketika Saya bertanya, kapan mulai kerja di Cafe? Sebelum mengelolah Kafe itu Jo sudah tinggal disana.
Semua berawal ketika Ia dikeluarkan dari Indekosnya tanpa alasan oleh pemilik rumah indekost. Lantas “Saya mengalami kondisi yang sangat sulit terkait tempat tinggal. Lalu [kondisi] ini diketahui oleh kawan-kawan Saya, termasuk pengelolah Cafe ini”. Imbuhnya.
Pengelolah Kaffe itu mengizinkannya untuk tinggal di sana sampai Ia menemukan tempat tinggal yang baru.
“Bro, kawan [pengelolah kafe] itu orang baik. Tanpa minta bayar, apa pun, saya diizinkan tinggal di kamar yang kosong,” pinta Jo penuh kagum.
“Kejadian itu di bulan November 2020.” Jelasnya. Jo hentikan pembicaraannya seketika.
Perempuan asal perbatan negara Papua New Guinea dan Indonesia itu masih duduk terdiam disana. Posisi kepala agak naik keatas berporos 30 derajat dari posisi berhadapan tadi. Wajahnya agak menoleh ke samping. Lantas Ia perlihatkan senyuman tipisnya dengan jelas seakan sengaja Ia membiarkan terurai begitu saja si pemilik pipi cokelat itu. Lalu mengambil sebatang rokok, lalu meletakannya di mulut, menahannya dengan kedua bibirnya merapat sangat menggoda. Sementara tangan kirinya menyusul ambil korek api. Mengangkat tangannya, persis cara Che Guevara membakar rokok cerutu di film biografi che.
Tampak diam, menahan sesuatu didalam sana. Belum beberapa detik, Ia semburkan asap rokoknya seraya meregangkan otot diafrakma yang tadinya kencang.
Jo mulai membuka cerita setelah meneguk sesekali kopi Pegubin-Papua.
Selama tinggal di Kafe itu, pengakuannya, Ia merasahkan sesuatu yang berbeda. “Merasahkan suasana yang tentang, tempatnya nyaman. Jauh dari kebisingan suara kendaraan. Dan tentu saya mengamati aktivitas di kafe ini. Selain pengunjung yang datang, juga bagaimana pelayanannya. Terkadang melirik cara mereka mengelolah kafe.” Jadi secara tidak langsung, menurut Jo, Ia mendapatkan ilmunya.
Lalu, dengan berjalannya waktu, suatu saat, Kaffe itu mau dijual karena mengalami masalah. Persoalan hutan-piutang yang belum kelar. Lantas, kata Jo, “Saya ikutan membantu menyebarkan poster tersebut. Saya posting di Story WA. Dan itu diketahui oleh keluarga saya di Papua juga. Termasuk Bapakde [Saudara sepupu dari bapak].”
Bapakdenya itu salah satu orang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, saat itu. Bisa dikatakan tergolong orang kelas menengah. Nah, Dia mau membelinya melalui perantara Jo. Kemudian Kafe itu dipercayakan kepada Jo untuk mengelolahnya.
“Sejak itu, kini sudah sebulan Saya kelolah.” Terang Jo sambil sesekali meneguk kopinya.
“Lalu bagaimana rasanya ketika Anda pertama kali mengelolah Kafe sendiri?” Tanya Saya penuh menaru rasa ingin tahu tentang hal-hal terkesan di awal kerjanya.
“Aduh, Bro. Masalah berat.” Jawabnya singkat.
Baru sebulan tetapi merasa banyak kekurangan, menurutnya. Masalah menajemen kafe, tata letak tempat, latar yang cocok, menurutnya, Ia tetap merasa banyak yang kurang dari pekerjaan itu. “Belum lagi persoalan utang yang belum dilunasi oleh pemilik sebelumnya; dan Saya mesti melunasinya,” lanjut Jo dengan wajah cemberut. “Tetapi ini tantangan pertama yang saya hadapi di dunia bisnis ini.” Pungkas Jo.
“Bro, Selain mengelolah Kaffe, kamu juga katanya aktif di pergerakan kiri. Kira-kira lebih tepatnya Saya sebut aktivis atau apa?” Tanya Saya, bersifat mengkonfirmasi.
“Yah. Begitu lah. Aktivis yang sedang pindah haluan ke dunia borjuasi. Hehehehhe,” ketawanya mulai tak tertahakan ketika menyebut kata “borjuasi” itu mengulang. Yah, aktivis tentu memusuhi borjuasi. Kerapkali mereka menyebut para penguasa dengan istilah borjuis. Sementara rakyat biasa disebutnya dengan kaum proletariat.
“Lalu, my Bro, kira-kira kapan bersentuhan dengan dunia Aktivis?” Tanya Saya dengan antusias.
“Waktu itu tahun 2015, saat itu perkuliahannya baru semester tiga.” Jelasnya.
Saat sebelum itu Jo tidak tahu-menahu soal Papua Merdeka dan baginya OPM itu tidak menguntungkan; justru banyak mengorbankan orang Papua; karena terjadi kekacauan, penembakan, dan mengganggu kelancaran pembangunan jalan dan kota, dan seterusnya. Itu yang ada dibenaknya, saat itu.
“Tetapi masuk ke dunia gerakan itu tentu mengubah cara pandang yang sebelumnya,” Teragnya.
Mengapa? Karena, lanjut Jo, sebelumnya Ia terisolasi dari pengetahuan tentang Papua saat masih di Papua. Padahal Ia berasal dari wilayah yang sangat bergolak tentang konflik ‘Papua dan Jakarta’. Sisi lain, Ia berasal dari keluarga elit. Bapaknya pejabat daerah. Mau kemana saja harus ada pengawalnya. Kemudian Ia sering kali dibatasi untuk bertanya atau menceritakan apa yang Ia lihat di jalan sewaktu pulang sekolah. Semisal tentang orang berdemonstrasi. Terkadang juga Ia merasakan perhatian orang tua didalam keluarga. Anak laki-laki itu selalu di lebih-lebihkan; di sayangi; di jaga karena dia yang akan meneruskan marga dari Bapak. Perempuan pasti dilihat sebagai penerus keturunan marga lain karena hukumnya harus menikah laki-laki dari marga lain atau keturunan lain.
“Eh, ko diam. Ko mau dapat tembak kah di Polisi?” ungkap Jo.
Pernyataan semacam itu selalu membatasi keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut. Selain Ia diharuskan untuk aktivitasnya ke sekolah, pulang, makan, belajar, bantu masak di dapur, dan betul-betul orang tuanya menerapkan konsep aktivitas pelajar (remaja) yang sangat ketat.
Tetapi, baginya, semua mulai berubah ketika tiba di Yogyakarta. Terutama ketika gabung ke organisasi Mahasiswa di luar Kampus.
“Awalnya bagimana, bro? Iseng-Iseng atau kejar target seseorang atau seperti apa” Saya bertanya dengan penuh berpenasaran tentang kontak pertama dengan gerakan.
“Awalnya saya diajak untuk ikut kegiatan pendidikan politik dari organiasi Aliansi Mahasiswa Papua. Saat itu Saya ikut saja.” Jo mulai lanjut cerita.
Tetapi, menurutnya, sebelum bergabung ke Organiasi Mahasiswa, Ia sudah mendengar banyak stigma yang dibangun terhadap gerakan Mahasiswa tersebut. Hal itu bersumber dari, terutama dari mereka yang menganggap diri senior di organisasi kedaerahan asal Papua. Contoh yang paling dekat itu para senior dari organisasi Mahasiswa asal daerahnya.
Para senioritas itu sering mengatatakan bahwa ikut kegiatan di organisasi Mahasiswa itu pekerjaan yang berat. Nanti kamu dapat tugas yang membebankan kalian punya diri sendiri. Mestinya kalian itu harus fokus untuk kuliah.
Tetapi Ia mengiyakan tawaran untuk ikut kegiatan tersebut dengan alasan saat itu tak ada kegiatan lain, juga membosankan dengan aktivitas yang sebelumnya.
Proses rekruitment dibikin selama tiga hari. Dengan mengikuti pendidikan politik organisasi AMP menjadi jembatan pembuka jalan pikiran untuk melihat Papua lebih dalam.
Tetapi, menurutnya, Pendidikan politik hanya selama 3 hari itu waktunya sangat singkat untuk mengetahui semua hal. Syukurnya ada kawan-kawannya yang selalu ajak jalan, cerita, diskusi, belajar menulis, ikut pertemuan, konsolidasi hingga aksi massa. Dengan itu Jo semakin mengerti situasi tentang Papua. Bahkan memahami budaya berorganisasi yang menerapkan prinsip kesetaraan, non diskriminasi, demokratis, dan sebagainya.
Baginya, kawan-kawan disana [di dunia gerakan] itu unik. Mereka punya segudang ilmu pengetahuan dibalik penampilan yang biasa-biasa saja. Mereka selalu saling sapa dengan panggilan “kawan”. Kawan itu untuk semua orang, kawan bagi siapa saja. Tak pandang umur, tak memandang senior dan yunior; laki-laki atau perempuan, dan sebagainya. Prinsipnya siapa pun yang berjuang karena benci dengan penindasan, dan punya cita-cita yang, yakni perjuangan untuk menciptakan masyarat-manusia yang lebih baik, maka mereka adalah kawan.
Jo diam sejenak.
Saya membiarkan kesunyian itu tercipta begitu saja.
“Bagi saya Organisasi gerakan Mahasiswa itu sekolah. Siapa pun yang pernah saya ketemu dan akan bertemu dalam hari-hari perjungan, mereka adalah guru bagi saya.” Jelasnya dengan nada yang kendor seakan suara dawai tak lagi menghasilkan bunyi yang nyaring.
“Semua itu Saya menemukan di tempat dimana saya pernah dan sedang sekolah, yakni organisasi mahasiswa progresif.” Pungkasnya.
“Bro,” Saya hendak lanjutkan satu pertanyaan lagi untuk Jo. “Dari sebanyak pengalaman itu, adakah pengalaman yang terkesan saat Anda menjadi pengurus?”
“Tentu ada pengalaman yang menyenangkan, juga menyedihkan,” jelasnya.
Satu hal yang sangat membanggakan baginya adalah saat itu Jo bukan lagi dilihat sebagai seorang perempuan, tetapi sebagai kawan. Sebagai seorang pimpinan gerakan. Bagimnya, disitu Ia diuji untuk hadapi konstruksi sosial tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarki yang sangat mengakar di alam pikir orang Papua. Misalnya, perempuan tidak bisa memimpin; perempuan lebih emosional; perempuan tidak bisa tegas; suka menangis, dan semua itu pelabelan lama yang sudah melekat di masyarakat di Bumi Nusantara ini.
“Tapi, Bro, ada satu pengalaman yang sangat menguji kesabaran saya. Sampir hapir di titik keputusahan.” Jo mulai mengekspor ingatan yang masih tersimpan rapih di dalam pikirannya.
Itu disaat-saat menjalankan program pengorganisiran di beberapa titik kota Jogja. Saat itu Jogja sedang beramai-ramainya aktivtias penggusuran terhadap warga. Sebut saja Kulomprogo, Parangkusumo, dan beberapa tempat lagi. Kemudian kondisi internal gerakan lagi mengalami kekurangan anggota. Banyak yang jarang aktif, menurutnya, karena akibat demoralisasi, bosan, atau kesibukan pribadi lain.
“…pernah hanya 3 orang saja yang hadir disuatu pertemuan.” Ungkap Jo. Wajahnya yang cerah kini mulai berubah seperti mendungnya kota Yogyakarta.
Karena kondisi itu sehingga mereka merencanakan rekrutmen untuk anggota baru. Mulai dari logistik, print materi, konsumsi, pemateri, mengurus keberangkatan peserta, dan sebagainya. Semuanya sudah dibagi tugas kepada kawan-kawan.
“Tetapi pada hari pelaksanaanya, hanya kami dua orang saja yang hadir, Saya dengan Kawan Oni.” Ia lanjut bercerita. Entah kenapa suaranya mulai kehilangan kekuatan.
Sementara materi yang akan diberikan kepada calon anggota juga sangat banyak dan berat. Belum lagi persiapkan perlengkapan kegiatan, terutama soal konsumsi.
Saat itu Ia merasakan betapa sangat membutuhkan satu, dua orang kawan. Hal itu membuatnya hampir patah semangat. Belum lagi peserta dikpol yang datang terlambat, dst. “Tetapi saat itu saya lebih banyak mendengarkan lagu-lagu perjuangan. Lagu yang sering Saya putar berulang kali itu Judulnya: Doa Ibu di Revolusi.” Ungkapnya sambil menyekah air mata yang mengalir di pipinya.
Saya memilih diam saja. Membiarkan suasana ini berlalu begitu saja.
“Entah kena air mata Saya ini sulit dibendung, saat itu juga. Tapi Saya segera lagi ke kamar mandi untuk sudahi kesedihan ini.” Diam sejenak. Tangannya masih memegang ujung kerak baju sambil menyekah air mata. “Mama sudah pergi jauh. Dia pasti tersenyum dengan semua yang Saya lakukan untuk banyak orang, saat ini. Saya tidak menyadari akan seliar itu situasi kesedihan ini. Tetapi Saya betul-betul membutuhkan kawan, saat itu.” Jelasnya sambil menyekah pipihnya.
“Maaf, Bro, saa, saaya, minta maaf …”
Diam adalah jawaban Saya saat itu.
“Tapi bro,” Lanjut Jo dengan nada yang penuh datar seketika, “Saya mengakhiri dengan cepat dan tetap tampil bersemangat lagi.”
Akhirnya, mau tidak mau sesuai waktu yang sudah disepakati, pendidikan politiknya terlaksana.
“Bagaimana Anda jalani dimanika saat menjadi pengurus?” Tanya saya dengan penuh tak tega lempar pertanyaan lagi, seakan tak ingin terus-terusan mengorek informasi lebih jauh. Tetapi pertanyaan itu sudah terucap.
“Saya dipercayakan jadi ketua AMP Jogja periode 2018 sampai 2019.” Jelasnya.
Selain mengurusi AMP, juga aktif di organisasi Serikat Pembebasan Perempuan (Siempre). Pada 2017, Front Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) Wilayah Jogja membentuk Siempre sebagai sayap gerakan perempuannya. Saat itu Jo masih aktif di Biro Agitasi dan Propaganda di AMP Jogja.
“Tetapi semakin kesini, 2019 PPRI mandek. Dan itu berdampak ke program kerja Siempre.” Jelasnya sambil membakar sebatang rokok kretek kesukaanya seraya meneguk secangkir kopi yang entah sudah dingin atau masih terasa hanya serupa hangatnya cerita kita sore ini.
Sejak itu mereka mengerjakan program yang sudah disepakati bersama di Siempre. Misalnya pemutaran film, diskusi, memperingati hari Marzina, juga aktif terlibat dalam setiap peringatan hari Perempuan Sedunia atau Internasional Woman Day (IWD). Keanggotaan di dalam Siempre itu tidak dibatasi: Perempuan dari mana saja, ataupun laki-laki yang ingin bergabung.
“Bro, kita kembali ke dikusi awal eee? Hal apa yang mendorong/mendesak kamu terlibat dalam dunia bisnis?” Tanya Saya beberapa saat saling diam.
“Sebenarnya saya punya keinginan untuk membuat Cafe di Papua. Tetapi itu sebuah keinginan. Dunia sudah berkata lain.” Ungkapnya.
Tetapi, bagi Jo, saat ini ada peluang untuk Ia belajar. Baginya mesti banyak belajar untuk mengelola Cafe. Disisi lain tidak terlepas dengan hubungan personal yang bermasalah; juga kondisi keluarga. JO juga sudah yatim. Lalu punya tanggungjawab adik-adik dan anak yang harus diurusi.
“Kondisi hari ini Saya diharuskan untuk hidup mandiri. Saya menyadari bahwa Saya berada di titik tidak sejaya, dulu. Kondisi sudah berubah. Dulu butuh apa pun, tinggal minta ke orang tua. Sekarang harus lebih mandiri. Terutama soal urusan ekonomi.” Jo menjelaskan latarbelakang dirinya yang tentunya sangat sulit.
“Mungkin itu alasan lain.” Menutup pertanyaan Saya tadi.
“Bro, untuk saat ini lebih fokus ke Gerakan atau kelolah Kafe?” Pertanyaan terakhir Saya untuk menutup pertemuan ini.
“Aktif di organisasi, sebagai pengurus harian, tetapi juga mengelolah Cafe itu memang berat. Sangat berat untuk menjalankan dua peran dalam waktu yang bersamaan. Tetapi semua ini menurut saya semacam ada ujian untuk tetap kuat dan bersemangat. Karena organisasi juga sangat penting, tetapi urusan ekonomi macet, maka ini akan berdampak kemana-mana.
Tetapi organisasi juga sitem kerjanya kolektif, sehingga tidak harus saling komando. Semua program dijalankan sesuai kesepakatan di forum dengan membagi porsi kerja sesuai kemampuannya masing-masing. Karena itu Jo dan kawan-kawannya saling menguatkan satu sama lain.
“Tetapi satu hal yang selalu membuat Saya kuat, berani, adalah keyakinan.” Jelas Jo tentang prinsip hidupnya.
Tak terasa hari sudah gelap. Saya segera habiskan kopi yang tersisah di gelas lalu pamit pulang kepada Jo sambil say trims atas pertemuan hari itu. (*)